Ditulis oleh: Nur
Bintang*
"Saya lebih suka menganggap jika musik jazz
adalah seni intelektual"
(Nur Bintang, pengamat sosial dan budaya)
 |
| Savoy Saturday Nite, Gil Mayers, 1995 |
Pernahkah anda menonton film “THE TERMINAL” tahun 2004 yang
disutradai Steven Spielberg dan dimainkan
oleh aktor kawakan Hollywood yaitu Tom
Hanks? Film ini sebenarnya terinspirasi dari sebuah kisah nyata yang menceritakan
tentang kedatangan seorang pelancong yang bernama Viktor Navorski dari sebuah negeri di Eropa Timur di terminal airport John. F Kennedy, New York, Amerika Serikat. Cerita dalam film ini bermula ketika
kedatangan Viktor Navorski harus dilarang dan ditolak masuk ke Amerika Serikat oleh pihak imigrasi karena
pasportnya dianggap tidak berlaku dengan alasan negara asalnya sedang terjadi
kudeta, peperangan dan kekosongan pemerintahan sehingga statusnya dianggap
tidak legal.
Viktor Navorski yang diperankan oleh aktor
Tom Hanks kemudian membuat beberapa cara agar dapat meraih simpati untuk bisa lolos
masuk ke kota New York, Amerika Serikat walaupun harus menghadapi halangan-rintangan yang dibuat oleh
kepala bandara John F. Kennedy. Film ini sangat menyentuh dan humanis karena Viktor
Navorski datang ke Amerika Serikat hanya untuk melengkapi tanda tangan para musisi
jazz dari sebuah grup band jazz favorit almarhum ayahnya. Melalui
perjuangan dan dukungan kawan-kawan yang dikenalnya selama beberapa bulan di
bandara akhirnya Viktor Navorski berhasil mendapatkan izin resmi masuk ke Kota
New York, Amerika Serikat dengan tujuan untuk melengkapi seluruh tanda tangan dari seluruh personel grup band jazz tersebut yang
sebenarnya hanya tinggal tersisa satu buah tanda tangan dari seorang personel keturunan Afro-America, pemain
saksofon yang masih bekerja pada sebuah klub malam di sudut Kota
New York. Itulah sekelumit dari kekuatan dan daya tarik dari sebuah musik
jazz.
Saya sendiri mempunyai sedikit
kesamaan dari tokoh utama yang diperankan Tom Hanks di film “THE TERMINAL” tersebut karena saya
termasuk penggemar musik jazz. Saat saya berada di waktu santai dan rileks
terkadang membaca buku sambil mendengarkan beberapa lagu smooth jazz dari
musisi jazz kawakan seperti Nat 'King'
Cole melalui beberapa lagu “L-O-V-E”,
“Mona Lisa”, “Tenderly”, etc atau lagu-lagu dari The Cake hingga beberapa lagu jazz instrumental yang dimainkan oleh
beberapa musisi jazz dunia seperti Louis
Armstrong, Charlie Parker, Sidney
Bechet, dan Dizzy Gillespie melalui
suara merdu alat musik tiup trompet dan saksofon mereka. Entah apa yang membuat
saya betah terhadap musik jenis ini, dalam prinsip estetika saya bahwa semakin
rumit dan sulit sebuah lagu jazz untuk dipahami, didengarkan apalagi untuk
dimainkan maka lagu jazz tersebut akan semakin bertambah sexy di gendang telinga saya tanpa memandang siapapun latar
belakang komposer atau musisinya. Bagi saya musik jazz adalah musik kebebasan.
Musik yang berani mendobrak dogma, aturan dan pakem-pakem budaya lama bahkan musisi jazz besar Amerika seperti Charlie Parker sempat mengatakan
bahwa jazz adalah musik yang tidak bisa didefinisikan (JAZZ BE YOUR SELF!).
Musisi jazz 'Louis Armstrong'
Musisi jazz 'Louis Armstrong'
 | |
| http://0.tqn.com/d/jazz/1/0/-/3/-/-/LouisArmstrongHip_ORecords.jpg |
Musisi jazz
'Charlie Parker'
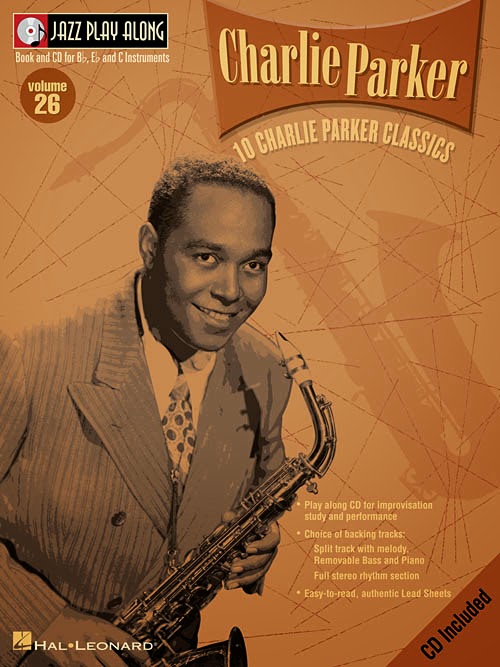 |
| http://s3.amazonaws.com |
Ketika membahas musik jazz saya jadi
teringat sebuah buku “Jazz, Parfum dan
Insiden” karya dari sastrawan besar Indonesia yaitu Seno Gumira Ajidarma bahwa jazz akan tetap hidup dan berkembang
jika ia membuka dirinya. Jazz adalah soal bermain jazz, bukan soal lagu apa
atau lagu siapa yang dimainkannya. Ada ulasan tulisan yang menarik dari Seno
Gumira Aji Darma jika musik jazz bisa berubah menjadi sebuah gaya, trend setter walaupun orang tersebut
tidak paham soal musik jazz yang penting nge-jazz untuk bergaya. Saya
berpendapat hal tersebut bisa benar adanya karena musik jazz menurut pandangan
saya secara konteks sosiologis terkini telah dianggap oleh masyarakat sebagai sebuah cita rasa seni, gaya hidup, seni multikultural,
musik postmodern, musik alternatif (avant-garde).
Sejarah jazz sebagai musik perlawanan yang berhasil menantang keangkuhan
‘budaya tinggi’ Eropa yaitu musik orchestra klasik, memang pantas untuk diapresiasi untuk semua kalangan penikmat musik.
Jazz bisa meraih penghormatan
seperti sekarang ini ternyata tidak terlepas dari banyaknya musisi jazz kulit hitam (Afro-America) dahulu yang
harus berpuluh-puluh tahun berjuang, merebut singgasana terhormat musik orchestra klasik yang sempat mendominasi
kebudayaan massa seluruh kawasan Eropa Barat terutama Amerika Serikat agar dapat berdiri sejajar dan
setara dengan budaya mereka (sebelum tahun 1920-an). Musik jazz lahir dan berkembang
dari peradaban kebudayaan kulit hitam di Amerika Serikat yang melalukan
perlawanan kultural dengan membuat budaya tanding (counter culture) terhadap segala bentuk hasil kebudayaan bangsa
kulit putih Eropa saat itu yang dianggap masih melakukan praktik diskriminasi, eksploitasi
dan penindasan terhadap bangsa kulit hitam di masa lalu. Nampaknya keberadaan
dan penampilan musisi jazz kulit hitam
di Amerika Serikat pada masa itu
memancarkan aura daya tarik alienasi
seniman dan warna kulit.
Sosiolog Yahudi-Jerman sekaligus filsuf,
musikolog, kritikus budaya aliran Mahzab
Frankfurt yaitu Theodor Adorno
pernah mengkritik musik jazz sebagai budaya rendah. Budaya rendah ini menurut Adorno
karena menganggap musik jazz hanya mencetak individualisasi semu dimana
industri label rekaman sebagai pihak kapitalis sudah membuat selera kebebasan
individu dalam memilih musik pop menjadi non standarisasi dalam proses
produksinya dan cenderung memanipulasi selera musik masyarakatnya. Akibatnya,
musik jazz menurut pendapat Adorno telah menjadi sebatas komoditas musik
hiburan produk industri untuk meraih keuntungan dari para konsumer seni. Namun saya secara pribadi menolak dan menentang
gagasan Adorno atas kritiknya terhadap musik jazz. Anti-tesis pemikiran
saya terhadap pemikiran Adorno bahwa musik jazz itu sendiri sebenarnya adalah musik
berbudaya tinggi. Jazz adalah suara nada indah dari Tuhan yang diwahyukan
kepada bangsa kulit hitam (Afro-America) untuk melawan segala bentuk
diskriminasi rasial dan penindasan budaya bangsa kulit putih Eropa terhadap
mereka di masa lalu. Klub malam dan rekaman musik nampaknya telah berubah
menjadi rumah ibadah dan media khotbah bagi para musisi jazz
kulit hitam saat itu untuk berkarya dan memberikan sentuhan hiburan bagi para
imigran masyarakat kulit hitam lainnya yang dilarang memasuki dan menikmati
tempat-tempat hiburan megah yang hanya boleh diperuntukkan kepada imigran bangsa
kulit putih Eropa di Amerika. JAZZ IS
POWER!
 |
| Musisi Jazz Afro-America |
Musik jazz di masa lalu memang selalu
dikonotasikan negatif sebagai wujud budaya rendah, kondisi pengangguran, pemberontakan,
kecemburuan sosial, pelanggaran hukum dari kacamata persepsi bangsa kulit putih
Eropa karena musik jazz saat itu banyak dimainkan di kawasan marjinal pemukiman
kumuh Afro-America terutama di kota-kota besar semacam New Orleans, Los Angeles,
Chicago, San Francisco, New York di Amerika Serikat. Apapun itu, Jazz memang lahir dan besar di
segala tempat dalam kondisi tekanan sosial, konflik sosial dan kriminalitas
tumbuh menjamur di kawasan Amerika Serikat di masa lalu seperti klub malam/bar
yang menjadi arena tempat perjudian, prostitusi, transaksi narkotika
dan segala stereotip negatif yang melekat terhadapnya. Namun saya tetap memandang jazz sebagai salah
satu ritual seni tinggi bangsa kulit hitam (Afro-America) yang dilakukan
melalui praktek seni kebudayaan yaitu permainan musik dalam usaha untuk merebut
makna harga diri dan identitas sosial serta melawan segala bentuk budaya penindasan.
Banyak musisi jazz kulit hitam dahulu yang bekerja di klub-klub malam melakukan
jam session dengan bermain musik, mengimprovisasi banyak lagu
untuk menghibur para pengunjung klub yang menari, berdansa, dan memesan
minuman. Bisa dibilang keberadaan pub, klub malam, bar saat itu menjadi ruang
eksistensi sosial bagi para musisi jazz kulit hitam untuk mengokohkan makna
identitas sosial dan kulturalnya di tengah penolakan sosial mayoritas imigran bangsa
kulit putih Eropa di Amerika Serikat terhadap kehadiran imigran bangsa kulit
hitam Afro-America.
Saya sempat membaca buku “Jazz 101 ; A Complete Going to Learning
& Loving Jazz” karya Prof. John
F. Szwed, seorang antropolog, musikolog ahli studi budaya Afrika dan budaya
Afro-America dari Universitas Yale,
Amerika Serikat bahwa sejarah jazz sendiri bermula dari sebuah rekaman
pertama oleh seniman jazz kulit hitam pada tahun 1915 namun sebenarnya musik
jazz sendiri berkembang di klub-klub bawah tanah di pinggiran Kota New Orleans
(1900-1925) terutama di daerah sekitar pelabuhan dimana banyak pekerja kulit
hitam yang menjadi pekerja (pengangkut barang) di kapal-kapal. Banyak ahli yang
mengatakan jika akar dari musik jazz berasal dari musik blues yang dimelodikan
dan dimainkan secara lebih serius seperti halnya musik klasik. Pada awalnya, musik
jazz banyak dimainkan pada acara perkumpulan sosial (pesta/dansa), parade,
pemakaman ataupun festival pada acara resmi di kota.
Memang tidaklah salah jika musik jazz
berkembang di Kota New Orleans karena pada masa lalu banyak yang menganggap
kota ini sebagai “The New of Athena”
dimana kota yang terletak paling bawah di negara Amerika Serikat ini merupakan
tempat terjadinya pertemuan kebudayaan yang beraneka ragam (budaya afrika - budaya
eropa - budaya latin) sehingga menghasilkan kebudayaan seni indah termasuk
musik jazz. Pada tahun 1917 terdapat grup musik yang bernama “Original Dixieland Jazz Band” dari New
Orleans yang memainkan jenis musik yang dinamakan jazz seperti yang kita kenal
seperti saat ini dan berhasil merekam beberapa lagunya di Kota New York.
Kemunculan band jazz legenda lain
seperti “King Oliver and Creole Jazz
Band” yang dimana pemain trompet sekaligus musisi jazz dunia yakni Louis Armstrong ikut menggawanginya
dengan banyak melakukan aksi solo melalui rhytem
section yang menjadi ciri khas mereka dalam beberapa pertunjukan secara live TV dan radio di Amerika Serikat.
Inti dari grup band jazz sendiri banyak mengadopsi dari marching band dimana kedudukan para pemain trompet, klarinet,
bahkan saksofon mempunyai tempat yang penting dalam sebuah band yang terdiri
dari drum, gitar, piano, dan bass. Jazz mendapat pengakuan sebagai bagian dari
representasi budaya Amerika pada akhir abad 20 dan berpengaruh menghilangkan
sekat batasan terhadap kelas sosial dan ras suku bangsa di Amerika. Berikut ini adalah
kronologi perkembangan musik jazz yang diambil dari buku “Jazz 101 ; A Complete Going to Learning & Loving Jazz”:
-Pra Jazz (1875-1915)
-Jazz New Orleans (1910-1927)
-Swing (1928-1945)
-Bebop (1945-1953)
-Cool Jazz/West Coast Jazz (1949-1958)
-Hard Bop (1954-1965)
-Soul/Funk Jazz (1957-1959)
-Modal Jazz (1958-1964)
-Third-Stream Jazz (1957-1963)
-Free Jazz (1959-1974)
-Fusion dan Jazz Rock (1969-1979)
-Neo-Tradisionalisme (1980-……..)
Saya
sendiri dahulu sebenarnya adalah seorang pemain bass (bassist) pada formasi grup band. Saya suka bermain bass dengan gaya funk memainkan beberapa teknik slap. Saya masih ingat dahulu bersama
teman-teman band ketika zaman kelas 2 SMA berhasil masuk final 10 besar dalam ajang
kompetisi festival band pelajar yang diselenggarakan oleh YAMAHA musik di Kota Purwokerto walaupun harus kalah dan bahkan
tidak pernah menang juara sekalipun namun ada kepuasan tersendiri bagi saya dan
kawan-kawan ketika itu bisa menyisihkan puluhan peserta grup band pelajar
lainnya. Namun saat ini, saya
memutuskan untuk berhenti bermain gitar bass lagi karena saya merasa jika dunia saya bukanlah di dunia musik dan selain itu, saya juga mengakui tidak mempunyai
potensi bakat yang hebat dalam bermusik namun saya masih senang membaca
biografi beberapa tokoh musisi jazz terutama pada pemain bass-nya. Bagi saya, musik jazz adalah musik hati, musik yang membebaskan jiwa. Berkembangnya musik jazz yang dimainkan para musisi
kulit hitam telah menjadi wujud resistensi budaya Afro-America terhadap dominasi budaya
Eropa di Amerika Serikat. Saya secara pribadi berpendapat jika musik jazz merupakan bentuk gerakan kebudayaan (cultural movement) dari bangsa kulit hitam (Afro-America) yang menuntut pengakuan hak-hak sosialnya di masa lalu.
Musik jazz saat ini sudah mendunia terutama di Indonesia yang konon dahulu musik jazz diperkenalkan masuk ke Indonesia pada awal abad 20 oleh para musisi jazz dari Philipina yang banyak bermain dalam pertunjukkan musik jazz pada hotel-hotel berbintang sewaktu zaman penjajahan kolonial Belanda. Saya terkadang suka mendengarkan beberapa jenis musik perpaduan musik etnik tradisional dengan musik jazz seperti beberapa musik yang dimainkan grup dan beberapa musisi jazz kenamaan Indonesia seperti grup band Krakatau atau permainan musisi jazz dari Bali yaitu Balawan, musisi jazz dari Yogyakarta seperti Djadug Ferianto, musisi jazz Purwokerto yaitu Bayu Wirawan merupakan sosok pianist jazz Indonesia sebagai art tatum yang piawai memainkan beragam improvisasi jazz modern hingga tradisional. Nama-nama mereka kini bahkan sudah terkenal di belantika komunitas jazz internasional.
Musik jazz saat ini sudah mendunia terutama di Indonesia yang konon dahulu musik jazz diperkenalkan masuk ke Indonesia pada awal abad 20 oleh para musisi jazz dari Philipina yang banyak bermain dalam pertunjukkan musik jazz pada hotel-hotel berbintang sewaktu zaman penjajahan kolonial Belanda. Saya terkadang suka mendengarkan beberapa jenis musik perpaduan musik etnik tradisional dengan musik jazz seperti beberapa musik yang dimainkan grup dan beberapa musisi jazz kenamaan Indonesia seperti grup band Krakatau atau permainan musisi jazz dari Bali yaitu Balawan, musisi jazz dari Yogyakarta seperti Djadug Ferianto, musisi jazz Purwokerto yaitu Bayu Wirawan merupakan sosok pianist jazz Indonesia sebagai art tatum yang piawai memainkan beragam improvisasi jazz modern hingga tradisional. Nama-nama mereka kini bahkan sudah terkenal di belantika komunitas jazz internasional.
JAZZ TASTE INDONESIA itu
yang sebenarnya saya suka dari lagu dan gaya permainan musik jazz dari musisi
Indonesia. Rasanya mendengarkan lagu-lagu jazz etnik tradisional yang diiringi
alat-alat musik tradisional seperti: gamelan, angklung, kendang, seruling bamboo etc dari para musisi jazz Indonesia benar-benar mampu
menunjukkan kekayaan seni dan budaya Indonesia kepada dunia dan jujur saya
merasa ikut bangga atas hasil karya intelektualitas dari mereka. Jazz adalah
fleksibilitas bermain musik dan keterbukaan terhadap semua ragam jenis alat
musik terutama juga terhadap para pendengarnya. Kita sendiri dapat menikmati musik
jazz dimana saja seperti menikmati pertunjukkan musik jazz di angkringan pinggir
jalan dengan konsep sederhana dan merakyat seperti yang sering diadakan di Kota
Yogyakarta atau pertunjukkan musik jazz mewah,ekslusif, elite dengan gemerlap
lampu seperti yang sering diadakan di panggung-panggung teater di Kota Jakarta.
Saya masih menganggap jika musik jazz rasa Indonesia saat ini termasuk musik
jazz kelas dunia yang intelektual, kreatif, unik dan original.
Jazz
dapat dikatakan sebagai seni pertunjukkan live
yang berbeda dari musik rekaman produksi label. Penikmat musik jazz sangat haus
terhadap bentuk improvisasi dan aransemen baru dari setiap penampilan live sebuah grup band jazz. Hal tersebut
seperti apa yang pernah sastrawan Seno
Gumira Aji Darma tuliskan dalam bukunya yang berjudul “Jazz, Parfum dan Insiden” yang menggambarkan seni instrument jazz pada bentuk bebop yang dimana setiap instrument alat musik tersebut akan bercakap-cakap,
berbicara, spontan menggunakan alur bahasa musik menurut selera dari musisi
sendiri. Bisa dikatakan bentuk bebop dalam musik jazz adalah sebagai bentuk
dialog antar alat instrument musik dengan mempermainkan ketertiban seperti
suara kacau, lepas-kendali, terpeleset, dibolak-balik, bersahut-sahutan yang
tidak direncanakan sebelumnya namun tetap enjoy
menjaga alur beat iramanya dengan
selaras. Semakin kacau, berisik dan selaras maka gaya permainan bebop pada
musik jazz akan semakin bertambah nilai artistiknya karena diperlukan
penghayatan dan pemahaman tinggi atas kejeniusan improvisasi dan aransemen dari
para komposer atau musisi jazz tersebut dalam berinteraksi terhadap para
penontonnya.
Representasi musik jazz di zaman
millennium kini berbeda dibandingkan kondisi pada zaman di masa lalu. Musik jazz saat ini identik sebagai keterbukaan,
kebebasan, elite, prestise, toleransi, multikultural, universal dan
intelektual. Jazz kini berubah wujud sebagai kebanggaan artistik dan
kultural. Jazz menjadi wujud seni kebudayaan postmodern atas segala hal yang
sudah pernah dilakukannya selama ini. Jazz telah berhasil dan mewujudkan
toleransi dan menentang segala bentuk rasisme. Terlalu dangkal jika kita
memahami musik jazz ini melalui bentuk dan segala simbol stereotip. Jazz adalah
musik sosial dengan segala ciri organisasi sosial Afro-America dalam wujud praktik
kebudayaannya yang kini berkembang luas melintasi dunia dan mempersatukan beragam religi, ras dan
suku bangsa. Jazz berhasil mendobrak dogma lama pemikiran Barat selama ini
dengan menghapus perbedaan peran para pemainnya dalam sebuah grup band. Setiap
musisi jazz bisa leluasa luas berimprovisasi tanpa batas menurut selera aransemen
dan intuisinya. Mungkin benar pendapat Prof.
John F. Szwed jika musik jazz merupakan seni yang terdokumentasikan paling
baik dalam panggung sejarah dunia.
*Nur Bintang adalah pengamat sosial dan budaya
ooo
.jpg)


.jpg)
.jpg)

.jpg)

